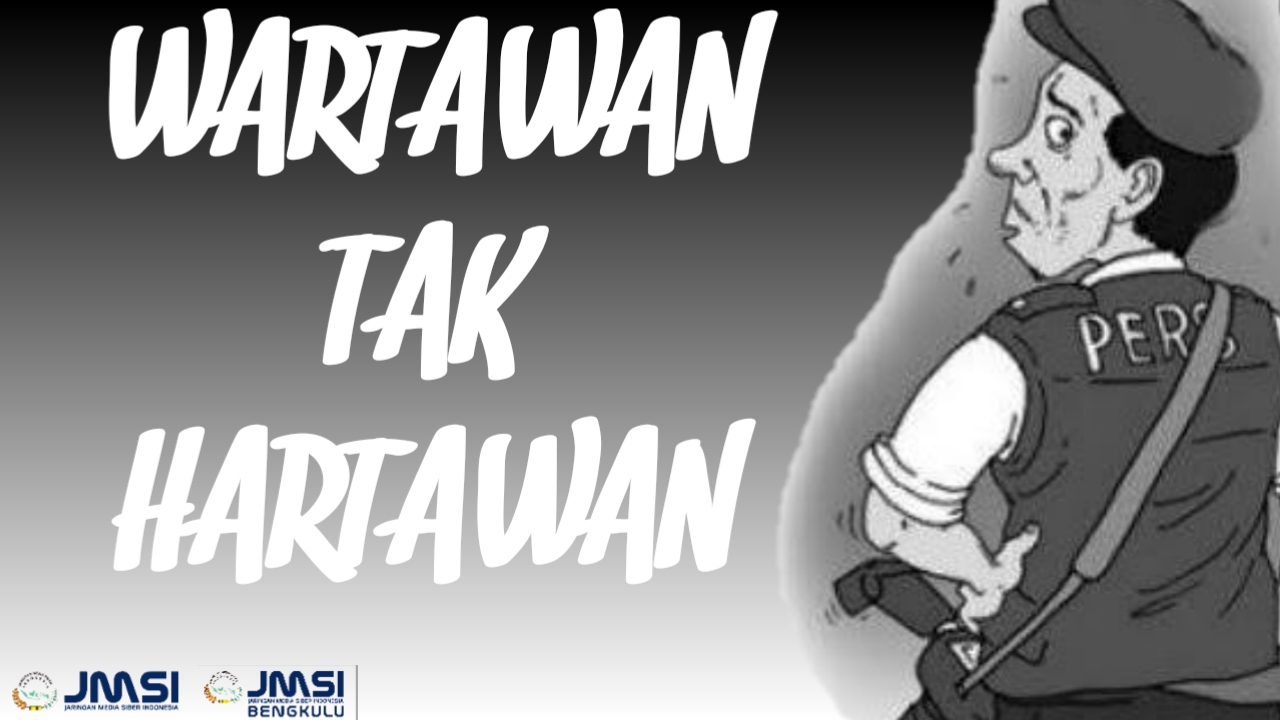Harga Sebuah Kelumpuhan: 60 Jam Kerja Sosial dan Luka yang Tak Tergantikan

Oleh: Wilzen Tra Apriza
Sebuah palu diketuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Curup, Rabu (4/6/2025) lalu. Suaranya mungkin terdengar biasa, tetapi gema yang dihasilkannya adalah sebuah pekik sunyi dari keadilan yang terluka. Di satu sisi, seorang remaja bernama Reza Ardiansyah (16) terbaring lumpuh, masa depannya direnggut paksa oleh pengeroyokan brutal. Di sisi lain, salah satu pelakunya, Dm alias Dimas, berjalan keluar dari pengadilan dengan vonis yang terasa lebih seperti teguran ringan daripada hukuman: 60 jam pelayanan masyarakat dan kewajiban membayar restitusi sebesar Rp150.000.
Ya, Anda tidak salah baca. Seratus lima puluh ribu rupiah. Harga yang ditetapkan pengadilan untuk membantu menambal luka dari sebuah kelumpuhan permanen, dari sebuah rumah yang terpaksa dijual, dan dari utang yang melilit keluarga korban demi biaya pengobatan.
Putusan ini, secara hukum, mungkin bisa dibenarkan dengan dalih perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim tunggal Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., merujuk pada pidana bersyarat yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Humas PN Curup pun mengamininya, menyebut bahwa hakim pasti punya pertimbangan. Namun, mari kita sejenak keluar dari koridor pasal-pasal yang kaku dan bertanya dengan nurani: apakah ini keadilan?
Di mana letak keadilan ketika 60 jam membersihkan masjid dianggap setimpal dengan penderitaan seumur hidup? Di mana keadilan ketika uang Rp150.000—yang bahkan tidak cukup untuk membeli dua kali suntikan saraf seharga Rp857.000 per dosis yang dibutuhkan Reza—dianggap sebagai ganti rugi yang layak?
Ini bukan lagi soal hukum di atas kertas, ini tentang empati yang terkikis. Nestapa keluarga Rovi, ayah Reza, adalah potret nyata dari dampak kejahatan itu. Ia tidak hanya menyaksikan putranya yang dulu aktif kini tak berdaya, tetapi juga harus menjual satu-satunya atap di atas kepala mereka. Semua harta ludes, utang menumpuk, demi satu harapan: melihat Reza sembuh.
“Hancur hati kami melihat kondisi anak,” lirih Rovi. Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan badai kepedihan. Enam kali mediasi gagal karena pihak pelaku tak sanggup (atau tak mau?) menanggung biaya pengobatan hingga tuntas. Harapan mereka satu-satunya kini bertumpu pada hukum. Namun, hukum justru memberikan jawaban yang terasa seperti sebuah lelucon pahit.
Sistem peradilan anak memang dirancang untuk restorasi dan rehabilitasi, bukan balas dendam. Tujuannya mulia: memberi kesempatan kedua bagi anak yang tersesat. Namun, prinsip keadilan restoratif juga menuntut pertanggungjawaban yang sepadan dan pemulihan bagi korban. Ketika hukuman yang dijatuhkan terasa begitu jomplang dengan penderitaan korban, maka tujuan restorasi itu sendiri telah gagal. Vonis ini seolah mengirimkan pesan berbahaya: kekerasan brutal oleh remaja bisa ditebus dengan harga yang sangat murah.
Kita tidak sedang menuntut darah dibayar darah. Kita menuntut agar hukum tidak buta terhadap air mata dan penderitaan nyata. Restitusi seharusnya tidak menjadi sekadar formalitas simbolik, melainkan upaya konkret untuk meringankan beban korban. Pidana pelayanan masyarakat seharusnya diiringi dengan pembinaan intensif yang benar-benar mengubah perilaku, bukan sekadar aktivitas pengisi waktu.
Putusan PN Curup ini adalah cermin buram bagi kita semua. Sebuah pengingat bahwa di antara tumpukan berkas perkara dan argumentasi yuridis, ada nyawa manusia yang nasibnya dipertaruhkan. Keadilan untuk Reza bukan hanya tentang menghukum para pelaku, tetapi tentang pengakuan dari negara bahwa hidupnya yang kini hancur memiliki nilai.
Sayangnya, putusan ini menilai kehancuran itu dengan harga yang tak bisa dibilang lain selain sebuah penghinaan.